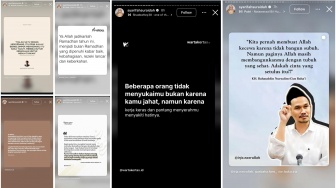SuaraKaltim.id - Menjalani profesi guru di daerah pedalaman, bukan hal yang mudah. Meski menjlani pekerjaan mulia, namun masih banyak guru yang hidupnya jauh dari sejahtera.
Hery Cahyadi misalnya. Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 011 Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartnegara (Kukar) ini pernah melalui getirnya perjuangan menjadi guru di pedalaman.
Sekolah yang dia pimpin berada di daerah yang terisolir. Namanya Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kukar. Desa ini merupakan daerah tanpa akses darat sama sekali. Semua harus dilalui menggunakan perahu kecil bermesin tunggal.
“Dulu, tak pernah berpikir bertugas di sini. Muara Enggelam itu apa, saya juga belum tahu,” kata Hery
Baca Juga:Nadiem Singgung Corona di Hari Guru: Setiap Peristiwa Selalu Ada Hikmah
Dia berkisah, pada tahun 1997 Hery baru lulus dari Pesantren Al-Mukmin di Kecamatan Muara Muntai. Hery ditugaskan untuk mengajar ngaji di Muara Enggelam, karena di daerah itu kekurangan guru baca tulis Alquran.
“Dulu Ustaz saya yang saranin. Karena bapak saya mengajar di Muara Enggelam, akhirnya saya ke sana dan di sana butuh pelajar TPA,” kata pria kelahiran Kayu Batu, 28 Agustus 1976.
Kala itu, orangtua Hery merupakan PNS di SD Negeri Muara Enggelam. Meski tak yakin ada jaminan masa depan, dia tetap pergi ke sana.
“Sempat setahun saya mengajar Iqro serta baca tulis Alquran. Akhirnya pada tahun 1998 saya saya dipertemukan jodoh di sini,” sebutnya.
Waktu-waktu pengabdian yang sesungguhnya dimulai. Pada tahun 1999, pemerintah membuka penerimaan guru honorer dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sejumlah sekolah dasar di kawasan pedalaman.
Baca Juga:Hari Guru Nasional, Simak 13 Fakta Mengenai Guru, Yuk!
Hery mendaftar dan diterima. Namun, tugasnya kali ini lebih jauh. Dia ditempatkan di Dusun Kuyung, Desa Sebemban, Kecamatan Muara Wis.
Bermodal niat kuat dalam mendidik adalah kunci bertahan mengajar. Itulah yang dirasakan Hery kala itu. Gaji pertama hanya Rp200 ribu.
Tidak cukup membiayai ekonomi keluarga. Agar asap dapur tetap mengepul, istrinya kadang menjadi buruh harian di pengepul ikan.
Tidak sampai hati pula Hery mengeluh, sebab warga pedalaman sangat membutuhkan kehadiran seorang guru. Sebisa mungkin warga pedalaman membuat guru yang bertugas nyaman dan betah.
Itu pula yang dirasakan Hery, meski honornya sangat jauh dari layak namun perlakuan warga sangat baik dan sopan.
“Kami disediakan rumah dan kadang diberi hasil tangkapan ikan mereka,” tambah Hery.
Jumlah guru yang mengajar sangat terbatas, hanya empat orang termasuk kepala sekolah. Tak heran jika satu guru bisa mengajar beberapa kelas.
Hery merangkap menjadi guru agama, pendidikan jasmani, hingga wali kelas tiga dilakukan bersamaan di sekolah itu.
Rasa Lelah kadang datang, apabila guru-guru berstatus PNS jarang datang mengajar. Beban mengajar menjadi tugas Hery sebagai guru honorer.
“Padahal di dusun itu ada guru PNS, tapi jarang masuk dan lebih sering menyuruh guru honorer. Mau tidak mau harus saya kerjakan semuanya, padahal masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri,” tambah Hery.
Di tahun 2000, Hery dimutasi ke Desa Muara Enggelam. Sebuah desa yang dibangun di atas aliran Sungai Enggelam yang langsung berhadapan dengan Danau Melintang.
Seluruh rumah dibangun di atas rakit. Tak ada daratan. Tidak ada akses darat. Namun Hery lebih bersyukur kala itu, sebab kampung itu adalah kampung istrinya.
“Lebih bersyukur, meski lebih jauh dari tugas sebelumnya, namun di desa ini merupakan kampung istri. Jadi bisa lebih nyaman,” kata Hery.
Sama seperti di tempat sebelumnya, guru PNS selalu mengambil libur kepanjangan. Apalagi kebanyakan guru tersebut bukan asli dari Muara Enggelam, sehingga semua pekerjaan dilimpahkan ke Hery.
“Sama saja kisahnya, saya harus menanggung beban mengajar lebih banyak,” kisahnya.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Hery bekerja serabutan. Menjadi nelayan tangkap air tawar adalah solusi terbaik kala itu. Dia juga sempat berburu kura-kura, bahkan sempat bekerja untuk NGO asing.
Menurut dia, masalah gaji kecil dan bertugas di pedalaman bukanlah hal mudah. Terlebih, harga kebutuhan sehari-hari tentu jauh lebih mahal. Kebutuhan susu juga mendesak karena anak sulungnya masih Balita.
“Pernah suatu kali kadaan sangat mendesak. Saya minta izin untuk mengajar tiga hari saja, sisanya saya gunakan untuk usaha apa saja. Alhamdulillah waktu itu kepala sekolah mengizinkan. Karena dia juga paham kondisi keluarga saya,” ungkapnya.
Derita lain menjadi guru honorer adalah gaji yang tidak tepat waktu. Bahkan kadang harus menunggu berbulan-bulan baru honor itu datang. Meski dirapel, tapi kebutuhan sehari-hari tak bisa menunggu rapelan.
“Pergantian nama dari PTT ke T3D (Tenaga Tidak Tetap Daerah) terasa sekali lelahnya jadi guru honorer. Gajian selalu tertunda, harus sabra,” kata Hery.
Sebenarnya, perubahan nama pada tahun 2001 itu berkah buat guru honorer karena gaji naik menjadi Rp325 ribu. Tak lama berselang naik lagi menjadi Rp480.480. Jumlah gaji yang gampang diingat dan bakal selalu dikenangnya.
“Meski gajinya naik, namun pembayarannya tidak tentu. Lebih sering tujuh bulan sekali, bahkan pernah menunggu sampai sembilan bulan baru gajian,” katanya.
Pada tahun 2007, kehidupan mulai berubah. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, diberlakukan pemutihan bagi tenaga honorer. Bagi Hery, ini adalah kesempatan untuk menjadi PNS.
Dia harus ikut tes hingga lima kali, hingga dinyatakan lulus. Pada tahun 2009 baru dia dinyatakan 100 persen PNS. Menurutnya, 10 tahun penantian yang tidak sebentar.
“Tidak ada yang instan, tak ada keistimewaan khusus. Semuanya saya lalui dengan proses yang Panjang,” ujarnya.
Kisah guru yang mengabdi di pedalaman, seperti Hery Cahyadi, adalah gambaran sesungguhnya sebuah pengabdian. Pengabdian dari seorang yang sering kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.