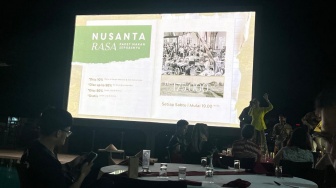SuaraKaltim.id - Dalam era serbacepat digital, informasi yang menyesatkan bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan kebenaran.
Lebih dari sekadar salah paham, hoaks di Indonesia telah terbukti menjadi pemicu konflik sosial, ekonomi, bahkan kerusuhan besar.
Hal itu ditegaskan oleh Ubaidillah, peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) BRIN dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Sosialisasi Konten Berdasarkan Riset: Menghindari Hoaks dan Disinformasi” di Samarinda, Rabu, 16 Juli 2025.
Ubaidillah mengangkat dua studi kasus dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menunjukkan betapa seriusnya dampak hoaks.
Baca Juga:Pekebun Rakyat Kaltim Tetap Sejahtera, NTP Tertinggi Meski Sedikit Turun
Salah satunya terjadi pada 2013, saat kabar bohong yang tersebar di grup media sosial berubah menjadi amukan massa.
“Itu berkembang dari isu personal menjadi kerusuhan sosial. Awalnya cuma soal perempuan yang berselisih dengan polisi, lalu disebar sebagai isu agama. Ini bahaya ketika tidak ada verifikasi,” ungkapnya.
Menurutnya, dibutuhkan lebih dari sekadar akses internet untuk melindungi masyarakat dari jebakan disinformasi. Harus ada jeda berpikir dan tradisi cek fakta yang kembali dihidupkan di tengah banjir konten online.
“Butuh waktu 30 detik saja untuk bertanya, ‘Benar nggak ya ini?’. Itu sudah cukup menyelamatkan banyak orang,” katanya.
Ubaidillah juga menyinggung sisi lain dari bahaya hoaks: kerugian ekonomi. Ia mencontohkan kasus pada 2022 ketika ribuan warga NTB tertipu janji bantuan dua ekor sapi dari sebuah koperasi yang mengatasnamakan program pemulihan ekonomi pemerintah.
Baca Juga:Nilai Tukar Petani di Kaltim Naik Sepanjang 2024, Sektor Perkebunan Jadi Motor Utama
“Ternyata itu tidak pernah ada dalam skema bantuan resmi. Tapi sudah terlanjur, lebih dari 22 ribu warga mendaftar. Akibatnya demo besar-besaran ke bupati, gubernur, bahkan ke kementerian,” jelasnya.
Ia menekankan, unggahan media sosial saat ini bisa jadi bukti hukum, dan dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang.
“Unggahan bisa jadi alat bukti di pengadilan. Hidup orang bisa berubah 180 derajat hanya karena satu postingan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ubaidillah juga mengangkat isu deepfake yang belakangan menyasar tokoh-tokoh publik.
Ia khawatir masyarakat dengan literasi digital rendah, khususnya kelompok usia lanjut di daerah, bisa menjadi korban manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Bayangkan orang tua di daerah yang sangat percaya dengan tokoh-tokoh ini. Mereka tidak bisa membedakan mana video asli dan editan. Ini sangat riskan,” ujarnya.
Yang menarik, Ubaidillah menawarkan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal sebagai “tameng” menghadapi hoaks.
Ia mencontohkan bagaimana budaya Jawa dan Sunda sejak lama mengenal prinsip verifikasi:
“Dalam bahasa Jawa, ketika mendengar kabar, orang bertanya ‘Sapa sing ngomong?’ (Siapa yang bicara?). Orang Sunda bilang, ‘Ti saha?’ (dari siapa?). Ini bentuk dasar dari verifikasi,” jelasnya.
Tradisi ini, lanjutnya, bisa menyentuh lapisan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh literasi digital formal.
“Nilai-nilai lokal itu bisa menjangkau generasi yang lebih tua. Jadi bukan hanya soal teknologi, tapi juga kearifan tradisi,” tambahnya.
Senada, Hanna Pertiwi, pendiri Yayasan Young Speaker Indonesia, menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam membangun ruang digital yang sehat. Ia mengkritik kecenderungan publik yang menjadikan media sosial sebagai wadah curhat berlebihan.
“Aku paham banyak yang lelah jadi perempuan, ibu rumah tangga, atau pekerja. Tapi jangan sampai semua itu dikonversi jadi postingan yang memancing simpati atau caci maki. Harus mulai dari diri sendiri untuk jadi inspirasi,” katanya.
Hanna juga menekankan pentingnya narasi positif dari tokoh-tokoh perempuan yang jarang terekspos.
“Jangan sampai media sosial hanya dipenuhi konten yang memicu drama. Kita butuh konten dari orang biasa yang bisa jadi luar biasa,” tegasnya.
Kontributor: Giovanni Gilbert