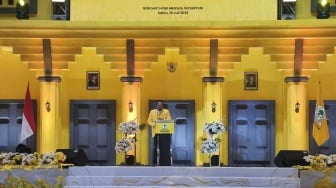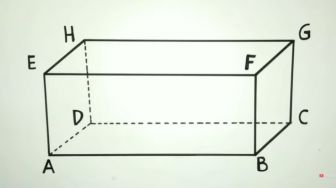SuaraKaltim.id - Kebudayaan kerap dianggap sebatas tarian, musik, atau pakaian adat.
Namun di balik itu, budaya menyimpan potensi strategis yang mampu menjadi fondasi pembangunan sosial, pelestarian lingkungan, hingga kebangkitan ekonomi kreatif berbasis lokal.
Hal inilah yang coba digaungkan dalam gelaran Helo East Festival 2025 di Kalimantan Timur (Kaltim).
Festival dua hari ini bukan sekadar ajang pertunjukan seni, tapi menjadi ruang interaksi antar komunitas dari berbagai latar—mulai dari pelestari budaya, pegiat lingkungan, hingga insan kreatif muda.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Bidik Jalan Perkebunan Jadi Akses Pesisir Strategis
Mereka berkumpul membawa semangat baru: bahwa budaya dan alam adalah satu napas, saling menghidupi.
Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kaltim-Kaltara, Thea Lestari, inisiatif seperti Helo East Festival mendorong lahirnya kesadaran baru tentang budaya.
“Selama ini kita mengenal budaya hanya sebatas kesenian atau tarian. Padahal mencintai lingkungan adalah bagian sangat erat dari kebudayaan,” ujarnya, Jumat, 18 Juli 2025.
Thea menggarisbawahi bahwa dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat sepuluh objek utama (OPK), dua di antaranya langsung terkait kelestarian lingkungan: pengetahuan dan teknologi tradisional.
“Kalau kita bicara 10 OPK, di situ ada pengetahuan dan teknologi tradisional. Ini sangat terkait dengan bagaimana masyarakat menjaga dan hidup berdampingan dengan alam,” katanya.
Baca Juga:Musda XI Golkar Kaltim: Aklamasi di Depan Mata, Konsolidasi Diperkuat
Data BPK mencatat, Kaltim sudah mendaftarkan 54 warisan budaya tak benda secara nasional, termasuk Museum Mulawarman dan Lamin Pemancung sebagai cagar budaya tingkat nasional.
Ada pula kekayaan budaya seperti tari jepen, musik sapek, tradisi belian bawo, hingga kuliner khas seperti petis dan sop tekalon.
Namun kekayaan ini, kata Thea, tak akan hidup jika hanya disimpan. Ia mendorong generasi muda untuk menjadi penggerak.
“Saya mintanya anak muda nih. Mari kita gali warisan nenek moyang, kembangkan dan manfaatkan untuk kepentingan bangsa ini,” ajaknya.
Thea memberi contoh potensi pengobatan lokal seperti kayu bajakah yang perlu digarap ilmiah, atau kuliner tradisional yang bisa naik kelas lewat sentuhan kreatif.
“Contohnya Sop Tekalo dari Paser, itu lebih segar dari soto. Nah, ini bisa diekstraksi bumbunya, dikembangkan plating-nya, dan dijadikan produk ekspor,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengajak para pegiat desain, digital, dan teknologi informasi untuk menghidupkan cerita rakyat menjadi karya populer, seperti animasi dan game.
“Kenapa kita meniru anime dari luar? Kita punya banyak pahlawan dari cerita rakyat. Pesut Mahakam bisa jadi ‘Pesut King’. Jagoan-jagoan dari tradisi Dayak bisa dibuat seperti Mobile Legends,” ucapnya sambil tersenyum.
Untuk mendukung misi ini, BPK membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan tidak hanya milik pemerintah. Komunitas, pelaku kreatif, masyarakat juga harus terlibat. Kami sangat terbuka untuk bergandengan tangan,” tegasnya.
Saat ini, BPK Wilayah XIV tengah mengusulkan Yupa sebagai bagian dari Memori Dunia UNESCO, serta Mando sebagai warisan budaya tak benda tingkat dunia.
“Kami mohon dukungan dari semua pihak agar Mando dan Yupa bisa diakui dunia. Ini akan menjadi kebanggaan Kalimantan Timur dan Indonesia,” harapnya.
Di penghujung pernyataannya, Thea menekankan pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai alat pembangunan, bukan sekadar ornamen pelengkap.
“Kebudayaan itu bukan objek yang dibangun, tapi alat untuk membangun bangsa. Kalau anak-anak muda bisa memimpin lewat kebudayaan, maka Indonesia akan sangat kuat,” tuturnya.
Nilai Tradisional, Senjata Ampuh Tangkal Hoaks Masa Kini
Dalam era serbacepat digital, informasi yang menyesatkan bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan kebenaran.
Lebih dari sekadar salah paham, hoaks di Indonesia telah terbukti menjadi pemicu konflik sosial, ekonomi, bahkan kerusuhan besar.
Hal itu ditegaskan oleh Ubaidillah, peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) BRIN dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Sosialisasi Konten Berdasarkan Riset: Menghindari Hoaks dan Disinformasi” di Samarinda, Rabu, 16 Juli 2025.
Ubaidillah mengangkat dua studi kasus dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menunjukkan betapa seriusnya dampak hoaks.
Salah satunya terjadi pada 2013, saat kabar bohong yang tersebar di grup media sosial berubah menjadi amukan massa.
“Itu berkembang dari isu personal menjadi kerusuhan sosial. Awalnya cuma soal perempuan yang berselisih dengan polisi, lalu disebar sebagai isu agama. Ini bahaya ketika tidak ada verifikasi,” ungkapnya.
Menurutnya, dibutuhkan lebih dari sekadar akses internet untuk melindungi masyarakat dari jebakan disinformasi. Harus ada jeda berpikir dan tradisi cek fakta yang kembali dihidupkan di tengah banjir konten online.
“Butuh waktu 30 detik saja untuk bertanya, ‘Benar nggak ya ini?’. Itu sudah cukup menyelamatkan banyak orang,” katanya.
Ubaidillah juga menyinggung sisi lain dari bahaya hoaks: kerugian ekonomi. Ia mencontohkan kasus pada 2022 ketika ribuan warga NTB tertipu janji bantuan dua ekor sapi dari sebuah koperasi yang mengatasnamakan program pemulihan ekonomi pemerintah.
“Ternyata itu tidak pernah ada dalam skema bantuan resmi. Tapi sudah terlanjur, lebih dari 22 ribu warga mendaftar. Akibatnya demo besar-besaran ke bupati, gubernur, bahkan ke kementerian,” jelasnya.
Ia menekankan, unggahan media sosial saat ini bisa jadi bukti hukum, dan dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang.
“Unggahan bisa jadi alat bukti di pengadilan. Hidup orang bisa berubah 180 derajat hanya karena satu postingan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ubaidillah juga mengangkat isu deepfake yang belakangan menyasar tokoh-tokoh publik.
Ia khawatir masyarakat dengan literasi digital rendah, khususnya kelompok usia lanjut di daerah, bisa menjadi korban manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Bayangkan orang tua di daerah yang sangat percaya dengan tokoh-tokoh ini. Mereka tidak bisa membedakan mana video asli dan editan. Ini sangat riskan,” ujarnya.
Yang menarik, Ubaidillah menawarkan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal sebagai “tameng” menghadapi hoaks.
Ia mencontohkan bagaimana budaya Jawa dan Sunda sejak lama mengenal prinsip verifikasi:
“Dalam bahasa Jawa, ketika mendengar kabar, orang bertanya ‘Sapa sing ngomong?’ (Siapa yang bicara?). Orang Sunda bilang, ‘Ti saha?’ (dari siapa?). Ini bentuk dasar dari verifikasi,” jelasnya.
Tradisi ini, lanjutnya, bisa menyentuh lapisan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh literasi digital formal.
“Nilai-nilai lokal itu bisa menjangkau generasi yang lebih tua. Jadi bukan hanya soal teknologi, tapi juga kearifan tradisi,” tambahnya.
Senada, Hanna Pertiwi, pendiri Yayasan Young Speaker Indonesia, menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam membangun ruang digital yang sehat. Ia mengkritik kecenderungan publik yang menjadikan media sosial sebagai wadah curhat berlebihan.
“Aku paham banyak yang lelah jadi perempuan, ibu rumah tangga, atau pekerja. Tapi jangan sampai semua itu dikonversi jadi postingan yang memancing simpati atau caci maki. Harus mulai dari diri sendiri untuk jadi inspirasi,” katanya.
Hanna juga menekankan pentingnya narasi positif dari tokoh-tokoh perempuan yang jarang terekspos.
“Jangan sampai media sosial hanya dipenuhi konten yang memicu drama. Kita butuh konten dari orang biasa yang bisa jadi luar biasa,” tegasnya.
Kontributor: Giovanni Gilbert